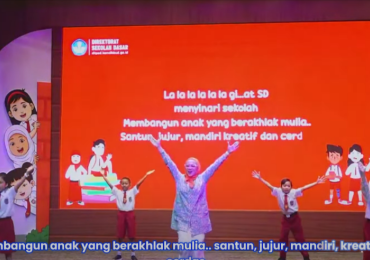Pendidikan Inklusif Solusi Mencegah Diskriminasi
- 10 Februari 2022
- Informasi
- Kunjungan: 37562

.jpeg)
Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya perbaikan mutu sekolah untuk mempromosikan pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua anak. Tidak hanya berfokus pada peserta didik pada umumnya tapi juga peserta didik yang memiliki keterbatasan dari segi latar belakang ekonomi maupun perbedaan kemampuan, dan salah satunya pada anak berkebutuhan khusus.
Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Hasil dari evaluasi Bappenas pada tahun 2017 menyatakan, bahwa kompetensi dan kesiapan guru menjadi salah satu penentu keberhasilan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
Selain itu juga warga sekolah perlu membangun lingkungan kondusif dan toleran terhadap perbedaan sehingga proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih optimal dan tanpa diskriminasi.
“Saya sangat mengapresiasi kepada satuan pendidikan sekolah dasar yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif. Terimakasih saya ucapkan kepada kawan-kawan kepala sekolah khususnya kawan-kawan dari dinas pendidilan kabupaten/kota yang sudah mendorong, mengadvokasi, memfasilitasi, serta mendampingi kawan-kawan di satuan pendidikan untuk siap menjadikan sekolahnya sebagai sekolah yang inklusif,” kata Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd dalam webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Rabu, 9 Februari 2022.
Ia melanjutkan, pendidikan inklusif ini harus dipersiapkan terhadap berbagai aspek yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tenaga pendidik yang harus disiapkan. Direktorat SD menilai terkait persoalan tersebut, satuan pendidikan harus ada kerjasama dengan pendidikan khusus sebagai pusat sumber untuk melakukan adaptasi peralihan dari pelayanan pendidikan reguler ke pendidikan layanan pendidikan inklusif.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah selain kesiapan kawan-kawan guru di satuan pendidikan dalam melayani putra-putri didik kita yang berkebutuhan khusus, penting juga pemahaman orang tua dan masyarakat sekitar serta stakeholder di satuan pendidikan memahami makna layanan pendidikan inklusif,” ujarnya.
Penerapan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan selain adanya kesiapan guru juga harus ada kesiapan fasilitas pendidikan. Oleh karenanya dengan tegas Sri Wahyuningsih mengatakan pemerintah harus mendorong agar setiap satuan pendidikan memiliki kepekaan terhadap pelayanan pendidikan inklusif, ada ataupun tidak ada peserta didik dengan kebutuhan khusus.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah sudah mendorong agar pendidikan umum secara bertahap haus memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dari sisi sarana prasarananya.
“Mari kita tingkatkan dan perbanyak sekolah-sekolah untuk dapat melaksanakan layanan pendidikan yang inklusif, karena pendidikan inklusif salah satu solusi mencegah diskriminasi. Tidak dapat dipungkiri implementasi pendidikan inklusif ini harus dimaknai dengan tepat sehingga pihak yang terlibat dalam pendidikan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anak di Indonesia,” tandasnya.
.jpeg)
Sementara itu Dr. H. Yaswardi, M.Si., Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menuturkan, ada 3 indikator yang harus diwujudkan dalam Merdeka Belajar. Pertama adalah sekolahkan anak-anak Indonesia. Pemerintah perlu mendata ada berapa anak Indonesia yang belum sekolah, dalam konteks berkebutuhan khusus apakah usia PAUS, SD, SMP, dan SMA.
“Ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah angka anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah masih tinggi,” kata Yaswardi.
Lalu indikator yang kedua, semua satuan Pendidikan harus mengenal 8 standar nasional pendidikan. Mulai dari standarisasi sampai dengan pembiayaan, peran guru dan tenaga kependidikan itu sangat signifikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
“Guru profesional itu salah satu dari 8 standar yang betul-betul harus diwujudkan di satuan pendidikan. Karena di saat kita bicara 8 standar pendidikan kita mengenal standarisasi, standar proses, standar asesmen, SKL, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, managerial kemudian anggaran,” ujarnya.
Kemudian indikator yang ketiga tidak ada yang tertinggal, harus ada distribusi yang merata baik secara geografis maupun sosial ekonomi. Dalam konteks Pendidikan inklusi seluruh anak usia sekolah dari lapisan apapun, baik bangsanya, agamanya, ras, domisili hingga status sosial ekonomi orang tuanya harus diberikan ruang kesempatan kepada anak usia sekolah untuk hadir di satuan Pendidikan.
“Bukan cuma hadir mendapat perlakuan yang sama namun juga dalam konteks sanjungan dan pujian, sentuhan-sentuhan serta kehangatan sangat dibutuhkan oleh anak Indonesia di saat dia mendapatkan layanan Pendidikan yang berkualitas,” katanya.
.jpeg)
Dalam kesempatan tersebut, S. Widyastuti, Center of Studies on Inclusive Education Sekolah Tumbuh menambahkan, sebagai sekolah inklusif pihaknya terus belajar salah satunya adalah dari buku Index for Inclusion. Dalam buku tersebut ada tiga hal untuk membangun sekolah dengan pendidikan inklusi. Yaitu kebijakan, kultur atau budaya inklusif kemudian ada praktek inklusif.
“Paling utama dari tiga hal itu menurut kami yang paling mendasari adalah yang membangun budaya positif dan saling menerima. Karena sebagai guru saya kerap menemukan anak-anak yang sangat beragam. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba mengenali mereka semua itu dengan baik melalui ngobrol dengan orang tuanya dan juga dengan assessment center,” tuturnya.
Dari mengenali murid secara dekat maka guru akan tahu apa saja yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Sehingga antara murid, orangtua dan guru dapat saling mengerti. Sementara itu anak yang mempunyai kebutuhan khusus bukan hanya menjadi tugas gurunya melainkan juga tugas warga di satuan pendidikan.
“Jadi membangun budaya positif kita harus bisa melihat dulu anak-anak yang memiliki banyak ragam, dekati dan kenali mereka hingga ke orangtuanya. Sehingga semua elemen bisa saling bersinergi untuk mewujudkan sekolah dengan lingkungan inklusif,” tutupnya. (Hendriyanto)
Penulis: Hendriyanto
Editor: Lailatul Machfudhotin
Kategori Berita
Berita Terpopuler
-
3 Rekomendasi Senam untuk Anak SD
06 November 2024
-
Sistem Baru Penerimaan Murid TA 2025/2026 Lebih Tr...
05 Maret 2025